SEPERTI RAWA
Aku pernah datang ke sebuah rawa. Tak sendiri, tentu saja. Ada kamu di sana, duduk bersisian di bibir sampan kayu yang sudah barut dan renta. Airnya tenang, terlalu tenang, hingga bisa melihat langit memantul dengan malu-malu. Beberapa eceng gondok terapung di dekat haluan, diam seperti tahu bahwa kami tak butuh keramaian. Di kejauhan, gunung berdiri seperti penjaga waktu, dan kereta tua melintas lambat—terdengar samar, seperti dengung cerita lama yang belum selesai dituturkan.
Waktu itu, orang-orang sedang memancing. Mereka duduk bersila, sebagian membawa anak-anak, sebagian sendiri, dan sebagian lain seperti tak benar-benar menunggu apa-apa. Aku hanya membawa kamu, tapi lupa membawa kail. Andai aku ingat, kita mungkin bisa menyisipkan kisah tentang ikan kecil yang menggigit umpan, lalu kita tertawa karena senar kusut atau karena umpan justru dimakan burung air. Tapi hari itu tak memberi banyak celah untuk sempurna, dan justru karena itu, aku mengingatnya.
Sampan bergoyang pelan saat kamu memindah duduk. Kamu tak bicara, hanya menunjuk arah langit yang mulai berwarna senja. Tiba-tiba sandal sebelah kirimu lepas. Ia jatuh begitu saja, ringan, seperti daun kering yang menyerah pada musim. Aku sempat mencoba mencarinya, menunduk, menggapai, bahkan menyibak permukaan air, tapi sandal itu telah memilih lenyap. Kamu malah tertawa, dan senyummu seperti debur kecil yang menenangkan: bukan tentang kehilangan, tapi tentang membiarkannya terjadi.
Kamu selalu seperti itu. Tidak pernah mengikat hal-hal kecil, bahkan pada sesuatu yang lekat di kaki. Katamu, yang jatuh tak selalu berarti hilang, dan yang hilang belum tentu tak bisa dikenang. Aku tidak mengerti saat itu, tapi kini kutahu maksudmu. Seperti rawa yang kita lewati: tak pernah bergerak, tapi selalu dalam proses menyimpan. Kamu adalah suara kecil di kepala yang tak bernada, tapi menggema lama setelah senyap.
Aku masih ingat bagaimana tanganmu bermain air, menciptakan riak kecil yang tak pernah selesai. Kamu tidak berkata apa-apa, tapi seluruh gerakmu adalah bahasa. Sesekali kamu menoleh, senyum itu hadir tanpa alasan yang bisa kutangkap. Bukan karena candaku, bukan karena pemandangan, tapi mungkin karena kamu tahu—ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara kita, seperti lumut yang menempel diam-diam di sisi sampan. Tak kentara, tapi ada.
Kita tak pernah membicarakan apa-apa dengan gamblang. Tapi aku mengingat setiap desah yang kamu hembuskan saat angin membuat kerudungmu meleyot. Aku mengingat bagaimana kamu duduk, bagaimana kamu sesekali menyibak eceng gondok seakan mencari sesuatu yang hilang di antara mereka. Aku mengingat semua itu bukan karena ingin mengingat, tapi karena tubuhku menyimpannya tanpa sadar. Seperti rawa yang menyimpan sandalmu, aku menyimpan kamu.
Jika hari itu adalah kenangan, maka kamu adalah satu-satunya alasan kenapa ia layak dikenang. Kamu membuat segala sesuatu tampak lambat, bukan karena waktu berhenti, tapi karena bersamamu aku ingin segalanya tak cepat selesai. Kamu membuat rawa menjadi lebih dari sekadar air tergenang—ia menjadi ruang tanpa ujung, tempat diam menjadi bahasa paling tulus. Kamu mengubah ketenangan menjadi desir, dan keheningan menjadi nadir.
Kini, setiap aku lewat rel tua atau mendengar bunyi kereta jauh, aku teringat tawa yang tak pernah terlalu keras, dan senyum yang tak pernah ditagih. Rawa itu mungkin tak berubah, eceng gondok mungkin sudah bertambah, dan sandalmu entah mengapung di mana. Tapi di benakku, semuanya masih di tempat yang sama. Dan kamu, masih duduk di sampan itu, menatap gunung dengan sorot mata yang tak pernah memintaku untuk mengerti—hanya cukup mengingat
Sampan itu masih terapung dalam benakku. Tanpa tujuan, tanpa kompas. Tapi selagi kamu duduk di ujungnya, tak perlu tahu ke mana air akan membawa. Kamu adalah rumah yang cukup kutatap dari kejauhan, dan tahu: pulang tak harus berupa tempat. Kadang, pulang adalah kamu yang tertawa karena sandalmu jatuh dan tak pernah ditemukan lagi.
Dan jika rawa itu pernah menyimpan apa pun dengan setia, maka itu adalah caraku mencintaimu—diam, dalam, dan tak tahu cara pulang.



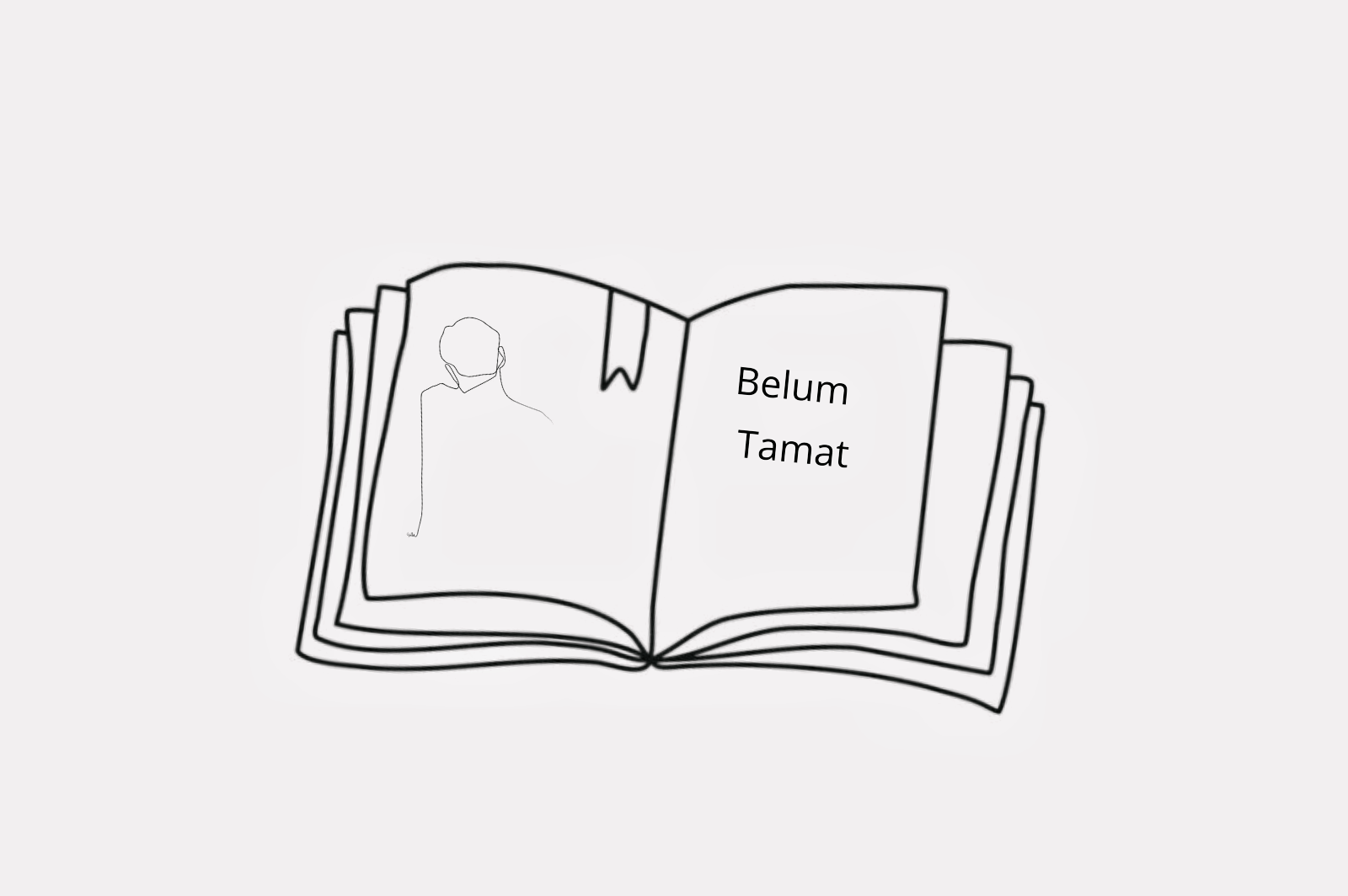


Komentar
Posting Komentar