SEPASANG KNITWEAR
Aku masih ingat, saat pertama kali kita membeli knitwear ungu muda itu, di toko kecil ujung gang. Bukan karena sedang tren, tapi karena katanya, warna itu membawa ketenangan bagi yang sedang patah. Berdua, kita tertawa kecil membaca filosofi warna dari brosur lusuh yang diselipkan penjaga toko. Waktu itu kita tidak percaya mitos, apalagi yang bilang baju kembar bisa membawa pisah. Tapi ternyata, ada yang tidak terlihat dari rajutan benang dan simpul perasaan kita.
Siapa percaya pada pakaian sama, hubungannya tidak akan bertahan lama? Bukan cuma baju, kita juga suka kopi yang sama: pahit di awal, manisnya muncul perlahan. Kita sering duduk lama di kafe langganan, bertukar cerita dan sesekali diam dalam nyamannya sunyi. Saling ejek soal siapa yang paling lambat membalas pesan, lalu tertawa seperti anak kecil yang baru jatuh cinta. Tapi bahkan tawa bisa berubah jadi gema yang kosong, saat hati mulai tak bersuara. Kini, bangku kafe itu masih ada, tapi tanpa kita.
Cinta kita aneh—begitu mirip dalam banyak hal, tapi tetap tak mampu bertahan. Dulu, perdebatan kita soal hal kecil seperti cara melipat baju atau memisahkan sendok dan garpu terasa lucu. Sekarang, aku bertanya-tanya: sejak kapan lelucon berubah jadi senyap? Sejak kapan jarak tidak lagi terasa ingin dijangkau? Atau mungkin, kita terlalu mirip, hingga tidak secuil pun menyisakan ruang untuk saling memahami?
Dalam diam, aku meraba bagian baju rajut itu yang kamu tinggalkan. Masih ada wangi parfummu, samar, seperti ingatan yang menolak pergi. Kata orang, hal-hal yang terlalu serupa bisa saling mengikis, seperti dua batu yang terus bergesekan. Tapi aku rasa, bukan kesamaan yang memisahkan kita—melainkan ketidakberanian untuk jujur. Kita terlalu takut mengakui bahwa cinta saja tidak selalu cukup.
Entah apa alasan pasti dari perpisahan ini—kamu pun tidak memberikannya. Kita seperti buku yang mendadak berhenti di halaman favorit, tanpa tahu akhir ceritanya. Mungkin memang harus begini: menyimpan kenangan, merelakan kehilangan, dan merajut ulang diri sendiri. Sepasang rajut itu masih tergantung rapi di lemari, jadi saksi bahwa kita pernah saling jatuh hati. Dan meski tidak sama-sama lagi, aku tetap menyukai kopi yang sama.
Fana memang semua yang bersifat dunia, tapi kenapa rasa ini masih menetap? Rasanya belum lama kita bercanda soal masa depan—rumah kecil, rak buku, dan secangkir kopi tiap pagi. Sekarang, yang tersisa hanya gema tanya dalam kepala: kenapa kita bisa berhenti, tanpa sebab yang benar-benar bisa dijelaskan? Aku mencoba mencari celah alasan di antara tawa kita yang dulu, tapi yang aku temukan hanya bayangmu yang perlahan menjauh. Dan anehnya, aku tidak bisa marah padamu, bahkan pada kepergianmu yang sunyi.
Gaduh kecil saat kita berbeda pendapat justru dulu yang paling aku rindu sekarang. Kita seperti dua musim yang berseberangan tapi tetap saling menanti. Ada sesuatu dari caramu menyanggah opiniku yang membuatku merasa hidup. Tapi kini, aku bahkan tidak tahu kabarmu—apakah kamu juga merindukan debat kecil itu, atau justru lega telah terbebas dari aku? Mungkin aku terlalu berharap, pada sesuatu yang dari awal tak pernah pasti.
Hari-hari tanpamu terasa aneh, seperti secangkir kopi tanpa aroma. Aku masih menyimpan semua hal kecil darimu: foto polaroid, struk belanja, dan tiket bioskop yang mulai pudar. Semua itu seolah mengendap, tak mau dibuang, tapi juga tidak bisa lagi dipeluk. Kadang aku tertawa sendiri mengingat betapa seringnya kita bertengkar soal siapa yang paling cengeng. Tapi kini, aku yang menangis diam-diam, hanya karena kamu tidak lagi di sini.
Ingatan itu seperti rajutan benang: jika satu tarikan meleset, bisa merusak seluruh pola. Mungkin cinta kita seperti itu—terlalu rapat, terlalu erat, hingga tidak ada ruang bernapas. Aku kadang bertanya, apakah knitwear ungu muda itu kutukan atau pertanda? Tapi lalu kuingat, kita yang memilihnya bersama, bukan karena mitos, tapi karena kita percaya makna. Sayangnya, kepercayaan itu pelan-pelan hilang, tidak sempat diselamatkan.
Jarak kini bukan lagi dalam kilometer, tapi dalam diam yang tak terjembatani. Kita sudah saling jatuh hati terlalu dalam, tapi entah kenapa, tidak bisa berenang di dalamnya. Mungkin karena cinta yang terlalu penuh justru tumpah. Atau karena kita sibuk menyesuaikan, hingga lupa bagaimana jadi diri sendiri. Yang jelas, rajutan itu masih ada—dan mungkin akan selalu begitu: hangat, tapi tidak lagi kita kenakan bersama.
Kalau nanti kita jumpa tanpa kesengajaan, kira-kira siapa yang akan mempertanyakan kabar terlebih dahulu?



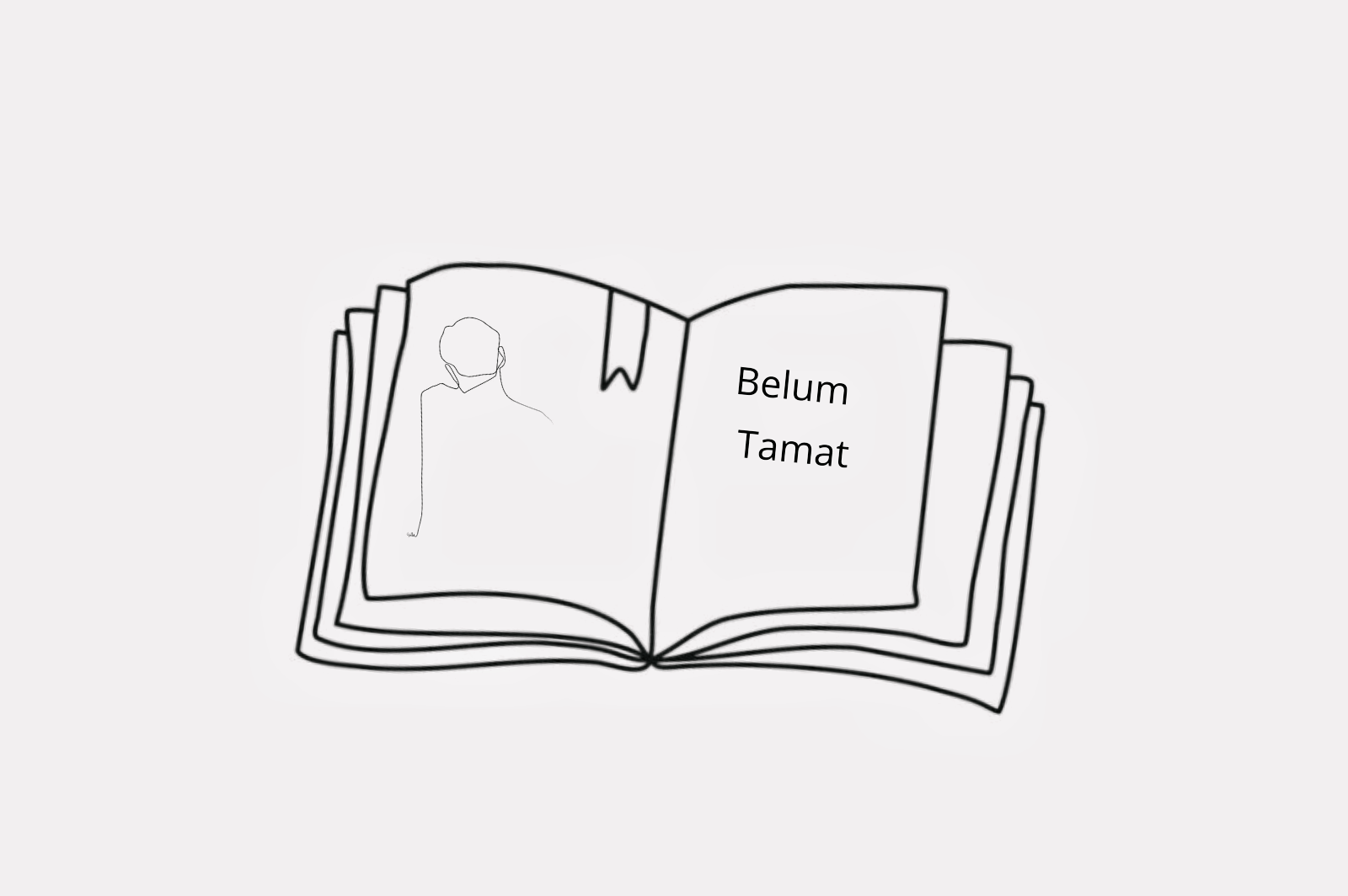


Komentar
Posting Komentar