KITA BELUM SEMPAT SALING
Setelah masa yang tidak bisa kusebut lagi cinta—karena bentuknya terlalu kacau untuk disebut begitu—aku menjadi lebih banyak diam. Orang-orang mengira aku pendiam, tapi sebetulnya aku hanya kehabisan cara untuk menjelaskan: bahwa ada reruntuhan di dalam kepala yang belum selesai dibereskan. Pernah aku dicintai, lalu dibohongi. Pernah pula dipercaya, lalu dijatuhkan. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi pandai menilai mana yang layak dijaga, dan mana yang hanya singgah untuk merusak. Aku tenggelam dalam banyak hari tanpa arah, seperti genangan yang tak tahu harus mengalir ke mana.
Lalu kamu hadir, tidak dengan suara, tidak dengan sapaan, hanya dengan keberadaan yang entah mengapa terasa menenangkan. Aku sempat berpikir untuk melangkah ke arahmu—bukan untuk menyuntingmu dari dunia, tapi sekadar memastikan bahwa kamu nyata. Aku ingin memilihmu. Bukan karena aku sedang sepi, tapi karena aku pernah percaya bahwa seseorang bisa membuat luka tak terasa sakit jika ia benar-benar tulus. Tapi ketakutanku tumbuh lebih cepat dari keberanianku. Aku takut menyakitimu dengan trauma yang belum sempat sembuh. Aku takut menjadi orang yang kembali gagal memperjuangkan.
Kita pernah bertemu, bukan sekali. Di persimpangan tangga gedung perkuliahan—kamu melangkah ringan, membawa tawa penuh semangat seperti iringan musik latar. Aku melihatmu di depan gedung astronomi, bibirmu sibuk berdialog dengan temanmu seolah-olah aku tahu apa yang sedang kamu bahas. Aku menjumpaimu duduk di kursi tunggu, dengan wajah tertunduk lesu, seakan membawa beban dunia yang tak bisa dibagi. Aku memandangimu dari atas gedung, saat kamu tiba di parkiran—dunia seakan berhenti beberapa detik hanya untuk pemandangan itu. Di samping mesin tarik uang, kamu berdiri dengan tangan menyelip di saku, seakan menunggu sesuatu yang tak pasti. Semuanya tampak biasa, kecuali perasaanku.
Paling kuingat adalah pertemuan tak sengaja di perpustakaan. Ruangan hening itu menjadi semakin senyap saat aku melihatmu masuk, dan aku terdiam lebih lama dari biasanya. Bukan karena tak ada kata yang bisa dikatakan, tapi karena aku tahu—aku bukan siapa-siapa untukmu. Tapi tetap saja aku berani melakukan hal yang mungkin tak patut: mengukir namamu diam-diam di rak penitipan tas. Hanya satu kata, tanpa inisialku. Bukan untuk dikenali, bukan untuk dikenang, hanya sebagai pengikat waktu bahwa aku pernah di sana, dan kamu juga. Mungkin yang kulakukan salah, tapi dalam sunyi itu, aku hanya sedang ingin merasa abadi, walau sebentar.
Aku bukan penguntit, bukan pula perangkai kata yang gemar menyembunyikan luka dalam bahasa yang berbunga. Aku hanya seseorang yang pernah mencintaimu dengan cara yang tidak bising, yang tak berharap lebih dari sekadar keberadaanmu di semesta yang sama. Aku tahu, keberanianku tak sepadan dengan perasaanku. Tapi dalam setiap langkah tak terucap itu, ada niat untuk menjaga, bukan menjebak. Aku ingin kisah ini—meski tak pernah dimulai—tidak runtuh tanpa makna. Dan jika aku tak pernah cukup dekat untuk kamu kenali, biarlah aku tetap di sana: di batas paling sunyi dari harapan.
Dan bila rasa ini harus menetap, biarlah ia menjadi danau tua yang menyimpan bayangmu dalam kejernihan yang tak pernah mengering.


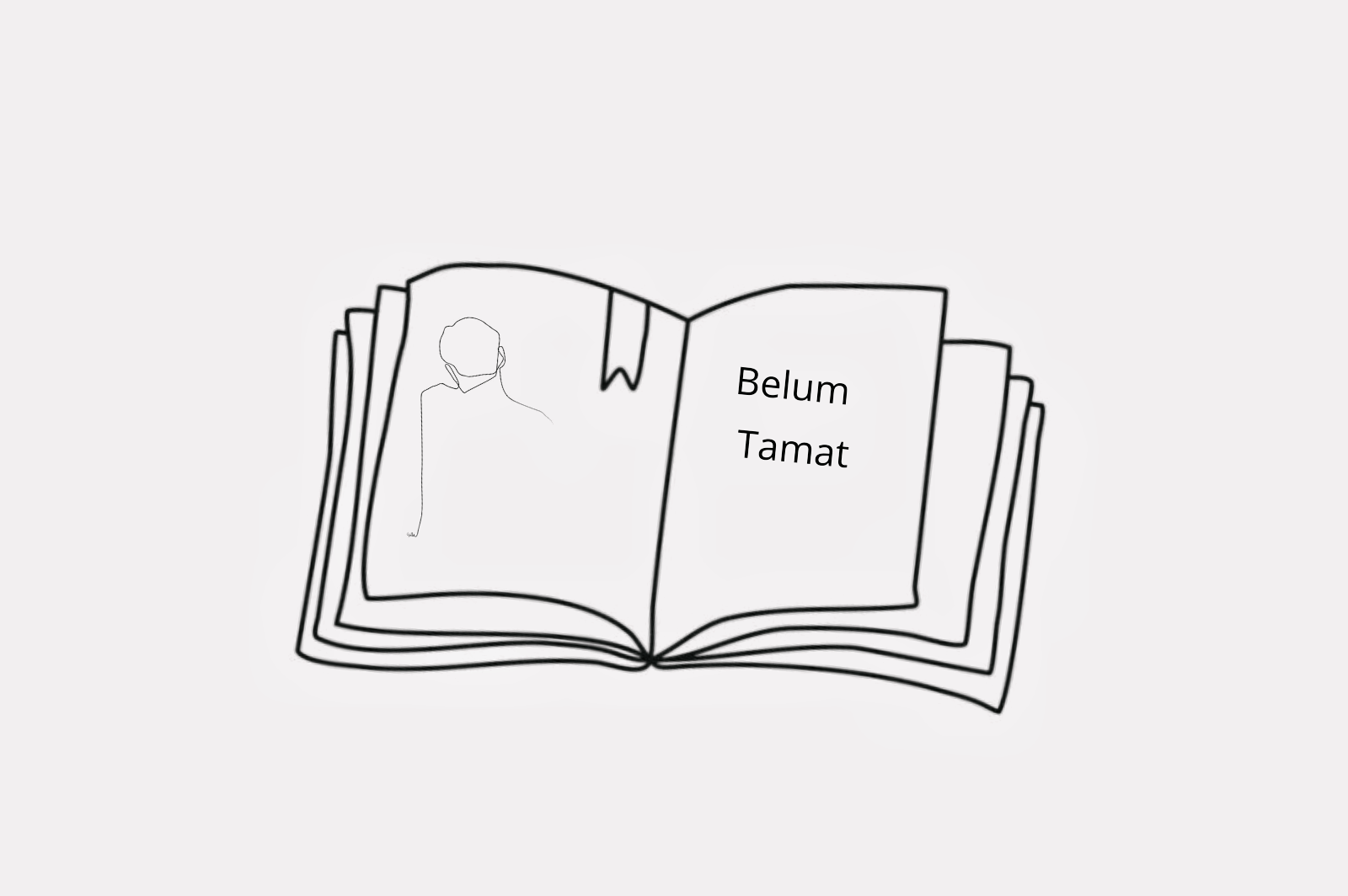


Komentar
Posting Komentar