KENAPA TIDAK MEMILIH MENJADI SEPERTI KARTINI?
Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan yang bercita-cita jadi perawat. Bukan perawat biasa. Dia ingin merawat dan mengajar di tempat yang tidak ada papan tulis, tapi banyak luka—dan muridnya adalah anak-anak perempuan yang lebih tahu cara menjaga tubuh daripada menjaga mimpi. Namanya tidak perlu aku sebut. Biarlah dia abadi dalam ingatan seperti Kartini dalam surat-suratnya.
“Aku ingin sekolah,” katanya padaku sambil menatap ke luar jendela, “tapi mereka bilang perempuan cukup tahu dapur dan ranjang. Cinta dan ibu rumah tangga. Tidak perlu gelar, asal tahu malu.” Berbicara tentang Kartini, tentang cinta, tentang tubuh yang bukan milik siapa-siapa. “Perempuan harus bisa berpikir,” katanya sambil membolak-balik halaman buku tebal yang tak pernah benar-benar selesai dia baca. “Tapi sekarang, banyak yang lebih suka diajak tidur daripada diajak diskusi.”
Aku tertawa kecil. Dia tidak. Matanya serius, seperti sedang memandangi dunia yang terlalu keras untuk dipeluk. Dia mencintai lelaki yang tidak pernah bisa membedakan antara pelukan dan perangkap. Yang mengira tubuh adalah tiket masuk ke keabadian, bukan rumah yang harus dijaga. Tampan, pintar, tapi takut pada perempuan yang terlalu lantang. Lelaki itu meninggalkannya setelah menyentuh bagian-bagian yang tidak semestinya disentuh dalam nama cinta. Lalu berkata: “Kamu bukan perempuan baik-baik.”
Dia menangis, malam itu. Bukan karena patah hati. Tapi karena dunia ini terlalu pandai menilai kehormatan perempuan dari hal-hal yang bisa disentuh, bukan dari isi kepala yang tak terlihat. “Aku ingin sekolah tinggi, bukan hanya agar pintar. Tapi agar bisa bilang ‘tidak’ dengan lantang. Tanpa merasa harus minta maaf karena jadi perempuan yang berpikir,” katanya.
Malam-malam dia habiskan dengan penuh lamunan, memikirkan tentang tubuh perempuan yang dicintai lalu dibuang. Tentang teman-teman sekelas yang tertawa karena rok ketat lebih dipuji daripada pikiran tajam. Tentang sahabat yang hilang setelah berpesta minuman keras, dan bangun dengan air mata.
Aku hanya bisa mengangguk. Kami tidak pernah berpacaran. Tapi dia tahu aku mencintainya. Dengan cara yang tidak pernah kusampaikan dalam bentuk rangkulan atau rayuan. Bukan dengan cara lelaki-lelaki itu, tapi seperti mencintai matahari: terlalu terang untuk digenggam, terlalu jauh untuk dimiliki, tapi selalu kucari di balik awan-awan muram hariku.
Dia tidak lagi di sini sekarang. Entah ke mana, mungkin ke negeri yang lebih adil pada perempuan. Mungkin sedang mengajar di desa yang listriknya tidak stabil, tapi hatinya terang. Mungkin sedang menulis surat panjang untuk dirinya sendiri. Atau mungkin sedang duduk di kamar sempit, mengingat-ingat masa lalu yang hampir membunuhnya, tapi juga membuatnya hidup.
Namanya tetap kudengar—di sela tawa mahasiswa baru, di sunyi koridor fakultas, atau di ruang diskusi malam hari. Dia hidup di setiap perempuan yang berani berpikir, mencintai, dan menolak tunduk. Kadang, aku masih menyebut namanya dalam do'a. Bukan agar kembali. Tapi agar tetap kuat. Tetap berjalan. Seperti Kartini. Yang tidak pernah mati.
Buku-buku Kartini dibaca wanita agar membuat dirinya lebih baik, dan lelaki membacanya agar bisa menghargai wanita dengan semestinya.
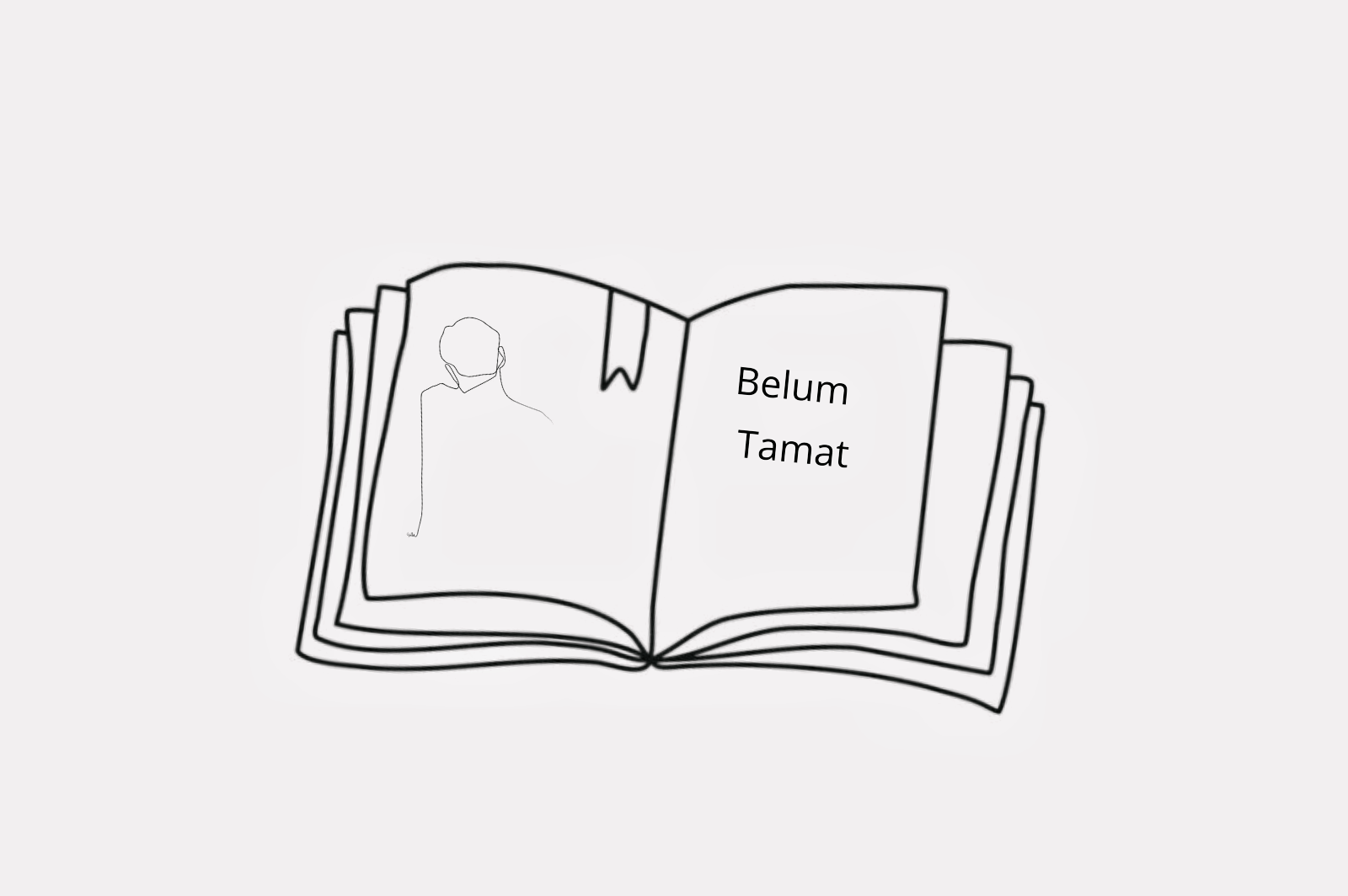


Komentar
Posting Komentar